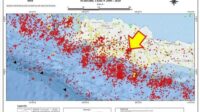Sulitnya Melahirkan Kader Radikal
Jika profil radikal yang dimaksud Menag adalah profil yang good looking, fasih berbahasa Arab, dan hafal al-Qur’an, maka ketahuilah bahwa profil dengan ketiga variabel sekaligus itu sungguh sangat sulit ditemukan. Jangankan dengan tiga variabel, dengan dua variabel saja juga tidak mudah. Kalau hanya good looking, mudah ditemukan di tempat-tempat menghias diri.
Namun, good looking dan bisa berbahasa Arab dengan fasih dalam masyarakat ‘ajam alias non Arab, itu hanya akan ditemukan di lingkungan pesantren, dan jumlahnya pun sekali lagi tidak cukup banyak. Good looking yang hafal al-Qur’an, jumlahnya lebih sedikit lagi. Sebab, menghafalkan al-Qur’an memerlukan usaha khusus yang kalau dibandingkan dengan menjadi sarjana, tidak ada apa-apanya.
Saya sering memberikan gambaran yang terlalu saya sederhanakan; kalau kuliah, asal datang, duduk, kemudian ngantuk sekalipun, akan lulus dengan nilai minimal C, atau bahkan B. Dan paling lambat lima tahun akan diwisuda jadi sarjana. Apalagi pada umumnya kampus sekarang berlomba-lomba memberikan kemudahan lulus, walaupun kualitas sering dikorbankan. Namun, untuk menjadi penghafal al-Qur’an, jangankan yang lebih banyak ngantuk, yang lebih banyak melotot matanya untuk menambah hafalan dan muraja’ah pun belum tentu sukses.
Saya ingin sekedar berbagai pengalaman dalam usaha melahirkan kader-kader yang hafal al-Qur’an. Tidak saya bedakan apakah mereka good looking atau tidak. Yang penting mereka sehat lahir batin dan memiliki daya ingat standar, maka akan saya terima sebagai peserta program menghafal al-Qur’an.
Upaya ini saya mulai pada tahun 2013. Dua tahun sebelumnya, tahun 2011, baru rintisan dengan puluhan mahasiswa yang saya kumpulkan dalam sebuah rumah perkaderan yang kami namakan Monash Institute di Semarang, persis di depan kampus III IAIN (kini UIN) Walisongo Semarang. Ternyata tidak semua mahasantri berani menghafalkan al-Qur’an.
Alasannya bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa terlalu berat menghafalkan 604 halaman. Menghafalkan juz 30 saja berat, apalagi menghafalkan 30 juz. Ada yang mengatakan takut tidak bisa menjaga, sehingga malah terjatuh dalam dosa. Keduanya sesungguhnya adalah alasan orang kalah sebelum berperang. Belum pernah berniat untuk bersungguh-sungguh untuk menghafal, tetapi sudah menyerah lebih dulu.
Namun, saya tak bosan memotivasi bahwa menghafalkan al-Qur’an dan menjaganya tidaklah seberat yang mereka bayangkan. Teks ayat bahwa Allah memudahkan untuk menghafal saya ulang hampir setiap saat mengajar, tanpa bosan. Juga saya ulang-ulang bahwa saya pun saat kelas VI sekolah dasar tidak bisa menghafal surat Yasin yang tidak terlalu panjang itu. Namun, setelah ada niat yang kukuh, akhirnya bisa menyelesaikan hafalan seluruh al-Qur’an. Alhamdulillah.
Tetap saja tidak semuanya mau menghafal. Hanya sebagian saja. Karena itu, pada penerimaan mahasantri tahun berikutnya, kami tetapkan bahwa salah satu syarat masuk dan mendapatkan beasiswa kuliah Monash Institute Semarang adalah bersedia untuk menghafalkan al-Qur’an. Dengan ada syarat itu, kami berharap secara mental mereka terkondisikan untuk menghafal sejak awal. Namun, sampai mereka lulus kuliah, yang benar-benar selesai menyetorkan hafalan 30 juz hanya bisa dihitung dengan jari sebelah tangan.
Alasannya bertambah lagi, dua di antara yang paling umum adalah sudah sibuk mengurus kuliah dan menjalankan aktivitas organisasi. Memang mereka saya wajibkan menjadi aktivis organisasi ektra kampus. Seolah itu adalah alasan yang wajar, karena berorganisasi saja sudah sering dijadikan alasan kuliah molor atau gagal, apalagi ini ditambah lagi dengan harus menghafalkan al-Qur’an yang tidak bisa disambi ngantuk.
Untuk lebih menekan mereka agar mau lebih serius, maka dibuatlah aturan baru yang terasa “mengancam”. Mereka yang tidak memenuhi target menghafal minimal 1 halaman per hari, maka tidak akan lagi mendapatkan beasiswa SPP. Tetap saja ternyata itu bukan jalan. Awalnya mereka terlihat mati-matian. Namun, itu hanya bertahan beberapa pekan saja. Keadaan kemudian kembali seperti semula. Mereka menerima saja beasiswa ditarik dan harus bayar SPP sendiri.
Kenapa saya berlakukan target yang ketat? Data yang saya pegang, menghafal al-Qur’an bisa diibaratkan dengan panjat pinang. Jika tidak total sampai atas, maka akan melorot ke bawah. Hafalan akan kembali hilang. Maka menghafal al-Qur’an harus total 30 juz dan setelah itu tetap memperkuat hafalan dengan melakukan sima’an harian di tengah apa pun agenda yang menjadi kesibukan.
Karena penasaran dengan argumentasi bahwa mereka disibukkan oleh agenda kuliah dan berorganisasi, maka saya buat program baru; Program Tahfidh 10 Bulan. Hitungannya gampang. Jika per hari konsisten menghafal 2 halaman, maka menghafal 1 juz yang terdiri atas 20 halaman hanya perlu waktu 10 hari. 3 juz bisa dihafal dalam waktu hanya sebulan. 10 bulan akan selesai.
Proyek pertama yang diikuti oleh tidak sampai 10 orang, menghasilkan dua orang yang sukses menghafal 30 juz. Yang lain masih di bawah harapan, karena maksimal hanya 23 juz. Namun, bagi kebanyakan orang, itu sudah capaian luar bisa yang jika ada kemauan kuat bisa dilanjutkan. Karena itu mereka tetap berada dalam pengawasan lanjutan.
Saya terus mencari penyebab lambatnya proses menghafal. Kemudian saya menemukan bahwa di antaranya adalah tidak ada penekanan kepada pemahaman kepada makna walaupun sekedar literal. Karena itulah, program menghafal berikutnya dengan mempersyaratkan menguasai makna literal. Peserta diberi waktu maksimal 1,5 bulan untuk belajar bahasa Arab al-Qur’an secara super intensif dan diajar oleh para mentor secara bergantian nyaris tanpa henti.
Yang berhasil, boleh menghafal. Sedangkan yang tidak berhasil, dipersilakan angkat koper, pulang. Sebab, jika tidak mengerti bahasa Arab al-Qur’an, kemungkinan gagal nyaris 100 persen. Lebih baik tidak, daripada mencoba sesuatu yang hasilnya sudah bisa diperkirakan. Agar tidak buang-buang waktu, pikiran, dan biaya, juga menyebabkan kepadatan asrama.
Ada peningkatan capaian, tetapi tetap saja belum sesuai dengan harapan. Mereka tetap memerlukan tambahan waktu lebih panjang dibandingkan yang telah dicanangkan. Daripada hilang, maka lebih baik memberikan perpanjangan dengan menambahkan lagi “ancaman”. Jika tidak menyelesaikan dalam waktu perpanjangan, maka akan dijatuhkan sanksi. Yang tadinya mereka masuk mendapatkan beasiswa atau gratis akan didenda sebesar jutaan, sesuai dengan kesepakatan.
Begitulah dinamika menghafalkan al-Qur’an. Yang hanya sekedar menyetor hafalan lalu hilang, memang cukup banyak. Angkanya bahkan bisa mencapai 80 persen. Namun, yang benar-benar menjaga hafalan sehingga mampu membacanya dengan lancar tanpa melihat teks, sangatlah sedikit. Maka simpulannya sangat sedikit sekali yang benar-benar radikal sebagaimana dimaksud oleh Pak Menag. Wallahu a’lam bi al-shawab.