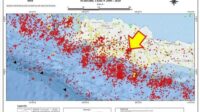Oleh: Dr. Sobirin Malian SH MH. Dosen FH Univ Ahmad Dahlan Yogya
Hajinews — Kekhawatiran perubahan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1919 akan melemahkan KPK terbukti benar. Perkara yang sangat besar yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan itjih Nursalim itu tiba-tiba dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Perkara itu sejatinya masih ditunggu-tunggu masyarakat bagaimana penyelesaiannya hukumnya, mengingat obligor Bantuan Likuditas Bank Indonesa itu ditengarai telah merugikan uang negara sebesar Rp 4,58 triliun.
Perubahan Undang-Undang KPK sarat Nuansa Politis
Sebelum membahas lebih detail terkait keluarnya SP3 itu, lebih dahulu penulis akan menyoal bahwa sejak awal adanya “niat” Presiden Jokowi mengubah UU tersebut, telah dicurigai bahwa perubahan UU KPK lebih kental nuansa politisnya ketimbang alasan “komitmen” penegakan hukum anti korupsi. Desakan DPR dengan nuansa transaksional-lah yang menyebabkan Presiden secara tiba-tiba menyetujui perubahan undang-undang KPK. Kala itu ada semacam “sandera” DPR kepada Presiden Jokowi bahwa jika UU KPK tidak revisi akan banyak hambatan yang akan dialami Presiden di parlemen terutama dalam kaitan dengan sejumlah legislasi dan hak kontrol DPR.
Di sisi lain, Presiden Jokowi sangat berkepentingan adanya koalisi besar di parlemen untuk memuluskan berbagai program dan kebijakan politik lainnya yang jika terhambat di DPR tentu akan mempersulit ruang gerak Presiden.
Tentu aspek politis seperti ini, jika dilihat dari sudut hukum tata negara, sangat merusak tatanan negara hukum. Dengan kata lain, secara teori dalam kasus “sandera menyandera” antara eksekutif dan legislatif yang berlaku adalah politik determinan atas hukum. Dengan demikian, kita bernegara dengan menafikan konsep negara hukum. KPK akhirnya lumpuh akibat desakan politik seiring dengan runtuhnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
SP3 KPK Bertentangan dengan Putusan MK
SP 3 KPK sudah dikeluarkan, tapi sadarkah kita bahwa SP3 itu sejatinya bermasalah. SP3 yang termuat dalam Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK itu, bertentangan dengan Putusan MK Nomor 06/PUU-I/2003. Putusan MK saat itu menyatakan bahwa KPK dilarang mengeluarkan SP3. Alasan prinsipnya jika KPK mudah mengeluarkan SP3, dengan kewenangan yang begitu besar dalam penanganan korupsi (extra ordinary) dikhawatirkan akan membuat KPK mudah menjadi sewenang-wenang dengan kekuasaannya (a buse of power). Oleh karena itu MK menetapkan KPK dilarang menerbitkan SP3.
Dalam kaitan, bagaimana jika KPK sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun kemudian hari ditemukan fakta bahwa bukti permulaan tidak cukup? Terkait hal ini, MK pun sudah pernah menerbitkan Putusannya. MK dalam putusannya waktu itu menyatakan,KPK tetap harus membawa perkaranya ke persidangan dan menuntut bebas pelaku tersebut.
Putusan ini dapat dipahami, mengapa ? Oleh karena KPK dibentuk sebagai lembaga extraordinary dengan kewenangan sangat luas. Konsekuensinya, KPK harus menganut asas kehati-hatian yang ekstra pula dalam menangani sebuah perkara.
Terkait penghentian perkara, sebenarnya tidak harus bermodal SP3. Dalam menjalankan tugas sejak tahun 2016 KPK sudah sering melakukan hal itu. Tercatat hingga tahun 2019 lalu, setidaknya ada 162 kasus telah dihentikan pada tahap penyelidikan.
Bahkan, KPK menurut undang-undang diperkenankan melimpahkan berkas penanganan perkara ke penegak hukum lain jika dirasa ada hal-hal yang tidak memungkinkan KPK menanganinya.
Misalnya, perkara yang ditangani kerugian negara dibawah Rp 1 milyar atau tidak ada keterlibatan penyelenggara negara (sesuai Pasal 11 ayat (1) UU KPK, jika KPK menangani tentu bertentangan dengan dasar hukum tersebut. Jika kasusnya demikian, kelanjutan perkara itu akan dikembalikan kepada penegak hukum lain, apakah akan dilanjutkan atau dihentikan dengan langsung mengeluarkan SP3. Praktik semacam ini pernah dilakukan dalam kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Isu krusial lain, terkait SP3 adalah,adanya pembatasan waktu penyidikan selama dua tahun. Pasal dan ayat ini banyak dikritik karena dianggap isinya naif. Bagaimana mungkin waktu penyidikan perkara korupsi yang sangat besar, kompleks dengan banyak aspek yang harus diselidiki,limit waktunya dibatasi. Pasal ini dianggap “simplikasi” terlalu menyederhanakan masalah.
Dapat dibayangkan, dalam kasus besar seperti BLBI ini, selain pencarian bukti memakan waktu lama karena tersebar di dalam atau luar negeri, juga banyak aspek yang harus divalidasi dengan kehati-hatian. Dalam konteks ini, jelas ayat ini terlampau menyederhanakan masalah atau bisa jadi “sengaja” dibuat demikian untuk mendapatkan jalan pintas. Koruptor pun tidak bodoh, terlalu mudah bagi mereka menyiasati pasal ini.
Bersembunyi di negara Singapura selama dua tahun, sudah cukup mengeliminir pasal ini. Padahal, seperti diketahui, kasus korupsi kerap menjerat pejabat yang kadang sulit (dipersulit) diproses hukum.
Kasus BLBI
Kasus ini diawali dari terbitnya SKL terhadap obligor BLBI yang telah lama menarik perhatian publik pada 1998. Pada saat itu, di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, banyak institusi perbankan terdampak dan masuk pada kategori sebagai Bank Take Over maupun Bank Beku Operasi. Di antara sekian banyak bank yang terancam bangkrut tersebut adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan pemegang saham pengendali (PSP) atau milik Nursalim.
Melihat kondisi saat itu, Bank Indonesia pun mengucurkan BLBI kepada BDNI sebesar Rp 30,9 triliun. Setelah dicairkan, dalam waktu tidak terlalu lama, pemerintah mencium gelagat yang tidak baik, karena adanya berbagai penyimpangan atas suntikan dana tersebut.
Setelah dianalisis, BI berkesimpulan memang ada indikasi yang dicurigai. Kemudian, BDNI diwajibkan melakukan penyelesaian melalui mekanisme Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).
Berdasar pada MSAA, terhitung jumlah kewajiban pembayaran Nursalim, setelah dikurangi seluruh aset miliknya adalah sebesar Rp 28 triliun.
Perhitungan ini menimbulkan masalah ikutan, yakni satu aset yang dijaminkan oleh Nursalim, yakni pinjaman kepada petani tambak senilai Rp 4,8 triliun, ternyata digolongkan sebagai kredit macet (misrepsentasi). Kesimpulan ini diambil berdasarkan Financial Due Dilligence (“FDD”) merupakan kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan oleh akuntan publik/konsultan keuangan terhadap suatu perusahaan mengenai kondisi finansial dari perusahaan target dalam hal ini perusahaan Nursalim. Setelah melalui audit tersebut, Kementerian Keuangan melakukan croscheck yang hasilnya pada tahun 2007, ternyata aset Nursalim hanya laku sebesar Rp 220 milyar.
Disimpulkan, selisih penjualan itu yang kemudian diklaim sebagai kerugian negara oleh BPK. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa aset yang sediakala sudah diketahui bermasalah, akan tetapi tetap diterbitkan SKL oleh Tumenggung yang kala itu menjabat sebagai Kepala BPPN.
Tumenggung sebenarnya memiliki cerita sendiri yang jika dikaitkan dengan kasus ini tentu banyak mengandung kejanggalan. Misal muncul pertanyaan, mengapa aset yang sediakala sudah diketahui bermasalah, akan tetapi tetap diterbitkan SKL oleh Tumenggung. Tentu hal ini, sangat ganjil. Uniknya lagi Tumenggung kala itu tidak dikenai pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan kasasi. Perspektif Pidana, unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tumenggung sudah jelas terlihat.
Misalnya, sebelum menjabat Kepala BPPN, Tumenggung sempat menduduki posisi sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Pada saat menjabat, Tumenggung sempat bertemu dengan Nursalim untuk menagih pembayaran hutang BDNI. Di samping itu beberapa hari sebelum SKL itu diterbitkan, Tumenggung selaku Kepala BPPN juga sempat mengusulkan pada forum terbatas yang dihadiri Presiden Megawati untuk menghapus (write off) hutang Nursalim. Namun, rapat tersebut tidak menghasilkan putusan apa-apa. Ini menandakan pemerintah kala itu tidak menyetujui usulan dari Tumenggung.
Tidak berapa lama, tepatnya pada tanggal 26 April 2004, Tumenggung resmi mengeluarkan SKL yang ditujukan kepada PSP BDNI, Nursalim.
Tumenggung sebenarnya juga menyadari bahwa dampak penerbitan SKL itu akan menghilangkan kesempatan negara untuk menagih Rp4,8 triliun dari Nursalim. Jadi, melihat perbuatan Tumenggung, dengan sendirinya unsur menghendaki dan mengetahui (willen en wetten) sudah terpenuhi. Sedangkan Nursalim, tentu harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab, sedari awal niat jahat (mens rea) dari yang bersangkutan ingin mengelabui negara dengan menjaminkan aset bermasalah.
Putusan kasasi menimbulkan masalah tersendiri terutama karena Tumenggung hanya dianggap terkait masalah perdata, bukan pidana. Lalu ihwal penolakan permohonan PK oleh MA juga menarik untuk dibincangkan. Meskipun telah ada putusan MK yang menyebutkan bahwa penuntut umum dilarang mengajukan PK, akan tetapi ada satu isu penting di balik vonis itu, yakni independensi hakim. Betapa tidak, salah satu majelis hakim terbukti melakukan komunikasi dan bertemu dengan kuasa hukum Tumenggung, sesaat sebelum putusan dibacakan. Artinya, bukan tidak mungkin vonis kasasi itu diwarnai dengan pertimbangan atau keadaan yang terlalu subyektif.
Pasca dikeluarkannya SP3, rasanya penting bagi KPK untuk segera memanfaatkan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait gugatan perdata. Regulasi itu menegaskan bahwa Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara tatkala tidak ditemukan cukup bukti, sedangkan di waktu yang sama telah ada kerugian keuangan negara, untuk selanjutnya dilakukan gugatan perdata. Ini penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Nursalim atas perbuatannya.
The last but not least SP3 KPK ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Saat ini korupsi BLBI sudah dihentikan, ke depan, bukan tidak mungkin akan ada perkara lain yang mungkin jauh lebih besar kerugian keuangan negaranya akan bernasib sama. Berangkat dari sini, jelas publik melihat substansi Pasal 40 UU KPK adalah bentuk pelumpuhan serius terhadap agenda pemberantasan korupsi.(*)