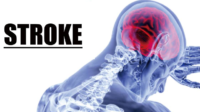Studi agama diperlakukan sebagai orientasi iman, dan karenanya dipelajari tanpa didahului dengan pengambilan jarak akademis-objektif yang memadai. Agama pertama-tama dilihat sebagai doktrin ideologis, bukan objek riset kritis dengan perangkat metodologis yang umum berlaku bagi semua objek keilmuan di semua bidang.
Azyumardi masuk gerbong pertama proyek ini bersama antara lain Bahtiar Effendy (belajar politik di Universitas Ohio), Din Syamsudin (belajar Islam di Universitas California), Komaruddin Hidayat (ke Turki), dan Amin Abdullah (juga ke Turki).
Memang jauh sebelumnya sudah ada sarjana Islam yang belajar ke Barat, seperti H.M Rasjidi (Prancis dan Kanada), Harun Nasution (Kanada), Mukti Ali (Kanada), bahkan Nurcholish Madjid (Amerika). Tapi kepergian mereka di tahun 1950-an, 60-an dan 70-an itu karena inisiatif pribadi, bukan bagian dari program pemerintah yang digariskan oleh seorang menteri agama.
Maka Azyumardi dapat dikatakan bagian dari generasi emas sarjana kontemporer Islam, khususnya dari UIN Ciputat, yang berkesempatan dididik di universitas bergengsi di Barat (Amerika). Ia belajar sejarah Islam di Universitas Columbia, mulai strata S2 hingga S3. Ia membuktikan kebenaran keyakinan Menteri Munawir. Ia lulus dari Columbia dengan disertasi gemilang yang kemudian menjadi karya klasik tentang jaringan ulama nusantara dan Timur Tengah di abad ke-17 dan 18 — sebuah studi yang mengharuskan ketekunan ekstra.
Tapi beasiswa pemerintah ternyata kurang. Penulisan disertasinya macet karena kehabisan biaya. Ia meminta tambahan dari Ford Foundation. Alan Feinstein, yang waktu itu manajer FF, bercerita bahwa bagi Azyumardi dana dari yayasannya lebih dari cukup, sehingga sebagian ia manfaatkan untuk naik haji. Jadi, kata Feinstein, sebagian pahala haji itu ia dapatkan juga — meski bagian terbesarnya tetaplah menjadi berkah bagi Azyumardi.
Sukses Azyumardi menandai sebuah era baru intelektual IAIN yang kehadirannya kemudian sangat mewarnai jagat pemikiran sosial-politik nasional, dan dapat dikatakan makin jauh meninggalkan reputasi para intelektual dari universitas-universitas sekuler. Ini gejala yang luar biasa diukur dari posisi pinggiran Ciputat — juga secara geografis, yang masuk Provinsi Banten, bukan Jakarta. Generasi-generasi sarjana UIN di bawah Azyumardi bermunculan dengan sangat subur; mereka bertebaran ke universitas-universitas Barat, termasuk Australia.
Dan dengan berubahnya IAIN menjadi universitas (UIN) di masa Azyumardi menjadi rektor di Ciputat (1998-2006), bidang kajian para dosen muda yang dikirim belajar ke luar negeri pun makin beragam, dengan ilmu politik menjadi primadona. Generasi Azyumardi seolah membukakan jalan lapang bagi mereka, dengan atau tanpa kelanjutan formal dari kebijakan Menteri Munawir Sjadzali.
Arena pemikiran politik Indonesia kemudian diwarnai oleh junior-junior Azyumardi seperti Saiful Mujani, Ali Munhanif hingga generasi di bawahnya lagi seperti Burhanudin Muhtadi dan Saidiman Ahmad. Memang tak semua anak-anak Ciputat itu meraih sukses gemilang, bahkan setelah mendapat peluang emas belajar di Amerika. Tapi secara umum kesuburan produktivitas Ciputat, tempat lahirnya Formaci, kelompok studi yang tangguh dan militan, menghadirkan potret baru yang menggembirakan.
Inspirasi UIN Ciputat juga melanda semua UIN lain, terutama UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, yang sejak lama memang menempati posisi terpandang, selain UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta.
Karir dan reputasi Azyumardi terus menanjak. Di tengah sayupnya suara Islam moderat di antara gemuruh kelantangan dan keterbelakangan wacana Islam abad 21 yang terus meningkahi laju perkembangan global, Azyumardi seakan tak kenal letih untuk menyuarakan Islam yang diyakininya, dengan argumen yang kurang-lebih akademis.
Sepanjang dekade 2000-an, kita berani memastikan tidak ada sarjana Indonesia yang melampaui prestasi Azyumardi dalam konteks undangan ke forum-forum mancanegara. Ia begitu sering tampil di forum-forum global di Amerika, Eropa, juga Jepang dan Asia Tenggara, dengan menyuarakan nada sama: bahwa Islam adalah agama damai yang sejalan dengan semangat kemanusiaan mondial, dan untuk itu orang luar perlu melihat the shining Islamic example of Indonesia, sebuah bukti kecocokan Islam dan demokrasi, bukan terpaku hanya ke Timur Tengah.
Kancah akademis mancanegara seperti berlomba ingin mendengar apa yang sedang terjadi di Indonesia, negeri berpenduduk muslim terbesar dan satu-satunya yang menjalankan demokrasi, tetapi selalu kurang terdengar di tengah keriuhan suara Islam Timur Tengah. Kekosongan itu berhasil diisi oleh Azyumardi dengan mengesankan; dengan daya juang dan kesabaran yang gigih. Ia menjelma jadi juru bicara Islam Indonesia (dan dengan demikian mendesakkan sebuah versi Islam non-Arab yang bisa universal pula), kurang-lebih dalam bentuk yang secara ilmiah bisa diterima oleh kalangan akademis Barat.