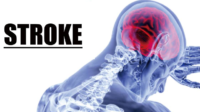Oleh: Fadhly Azhar, Mahasiswa Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wakil Sekretaris Lakpesdam PCNU Tangsel
Hajinews.id – Meski terjadi perbedaan waktu lebaran, Idul fitri 1444 H di tanah air tetap berupa momentum latihan kebatinan dan penegasan diri selaku insan spiritual. Alih-alih menajam dan segregratif, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk berlebaran dan saling bermaafan. Yang lebih dahulu atau belakangan dalam merayakannya disatukan oleh sikap dan penerimaan saling memaafkan.
Patut disyukuri, bangsa ini mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan urusan batin dalam diri warganya. Hal ini kemudian membangun kearifan bersama yang mampu menurunkan tensi ego lahiriah untuk berjalan, berkelindan, namun seimbang dengan kondisi kebatinan dan kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Hal demikian terlihat dalam lanskap historisitas lebaran dan makna halal bi halal dalam perjalanan bangsa ini.
Sejarah halal bi halal berasal dari KH Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1948. KH Wahab merupakan seorang ulama pendiri Nahdatul Ulama. Beliau memperkenalkan istilah Halal bi halal pada Bung Karno sebagai bentuk cara silaturahmi antar pemimpin politik yang pada saat itu masih riuh berkonflik.
Atas saran Kiai Wahab, pada Hari Raya Idul fitri tahun 1948 Bung Karno mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke Istana Negara guna menghadiri silaturahim yang diberi judul ‘Halal bi halal.’ Pada kesempatan tersebut, para tokoh politik akhirnya duduk satu meja.
Mereka mulai menyusun kekuatan dan persatuan bangsa ke depan. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah di masa pemerintahan Bung Karno menyelenggarakan “halal bi halal” yang kemudian mentradisi di Indonesia hingga kini.
Dari realitas tersebut, terbukti “halal bi halal” mampu berjalan dinamis dengan sejarah persatuan kebangsaan menuju “tobat-golongan”. Darinya, para pendahulu kita sudah mengajarkan keguyuban dan moderasi berbangsa dan beragama.
Meski berupa sarana latihan kebatinan dan upaya menjadi insan spiritual, Ramadan dan Lebaran tetap menyisakan pertanyaan kritis: mengapa muslimin perlu menjalankan puasa dan bermaaf-maafan setelahnya? Atas pertanyaan semacam ini, Imam Al Ghazali memberi pandangannya dalam kitab Arba’in fi Ushuluddin yang kemudian diperkuat kutipannya oleh Abdussamad Al-Palimbani dalam Kitab Hidayatussalikin.
Keduanya meyakini, puasa dalam diri mikrokosmos dan subtilitas manusia merupakan etape pelatihan diri yang paling efektif melawan penyakit atau maksiat batin. Maksiat batin tersebut berjumlah sepuluh, yakni tamak, cerewet, marah, gila kekuasaan, materialistis, pelit, sombong, narsisme berlebihan, riya’, dan hasud.