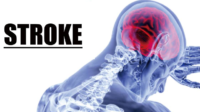Oleh: Agustinus Edy Kristianto
Hajinews.id – Koran-koran arus utama makin bicara tentang momentum pembenahan Polri. Seperti Kompas (23/8/2022) yang mengangkat pemeriksaan terhadap 83 polisi—tiga jadi tersangka—yang diduga terlibat upaya menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Ditulis bahwa relasi antarpolisi masih diliputi kekeluargaan sehingga saling menutupi kesalahan.
Saya kira masalah saling menutupi kesalahan sudah selesai sejak 2011. Ternyata, 11 tahun berlalu, bakteri demikian masih menempel.
Mungkin polisi belum bisa melupakan ketentuan Perkap 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang bunyinya: merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman, atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain (Pasal 9 huruf f).
Perkap 7/2006 sudah diubah lewat Perkap 14/2011 yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Kepolisian RI (Perpol) 7/2022. Sekarang setiap anggota Polri wajib melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang.
Saya tak tahu apakah aturan baru itu ampuh untuk melumat rasa ‘kekeluargaan’ yang menyimpang di tubuh Polri.
Rasa seperti itu sudah berkerak sejak lama, setidaknya sejak 8 September 1923, tak lama setelah Ratu Wilhelmina naik takhta dan Komisaris Besar Van Rossen—seorang polisi Batavia yang merupakan komandan wilayah Batavia dan Bantam—ditahan karena skandal korupsi anggaran kepolisian sebesar 1 juta gulden, selain menerima uang dari pusat perjudian dan pelacuran yang dikelola orang-orang Tionghoa serta pendapatan ilegal dari distribusi beras.
“Itu semua terjadi karena kuatnya sistem saling melindungi dalam kepolisian umum di gewest Batavia,” tulis Marieke Bloembergen dalam buku “Polisi Zaman Hindia Belanda” (2011).
Bagi saya, FS adalah salah satu contoh bagaimana sistem dan kekuasaan yang besar mempengaruhi pribadi orang untuk banyak berubah.
Contoh lain adalah tiga polisi yang saya kenal ketika menjadi penyidik KPK sekitar 14 tahun lalu dan saya pikir adalah orang yang baik integritasnya, saat ini malah ada di pusaran kasus FS: satu orang mantan Kapolres Jaksel yang mengumumkan skenario tembak-menembak dan baru saja diberitakan dikurung juga karena masalah etik; satu orang ditulis jadi komandan Project 2024 Kekaisaran FS; satu orang lagi tercantum sebagai pengepul setoran 303 Kelompok Medan dari kekaisaran sebelah.
Saya tak tahu benar-tidaknya cerita tentang kekaisaran di dokumen itu. Yang saya tahu adalah “Kerangka Langit” yang dibawakan band Kaisar.
Tapi FS tergolong muda dan cepat menaiki tangga jabatan Kadiv Propam Polri—lembaga yang anggarannya Rp107,7 triliun alias nomor tiga terbesar dalam RAPBN 2023, lebih besar dari anggaran Kemendikbud Ristek dan Kemenkes. Saya pikir masih lebih besar juga komposisinya jika dibandingkan dengan Kementerian Pertahanan yang Rp131,9 triliun tapi harus disebar ke TNI AL, AD, AU, belanja alutsista dsb.
Tak hanya anggaran tapi juga kewenangan yang besar. Selain kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan (termasuk di KPK, OJK dll), yang tentunya gurih adalah perizinan: izin keramaian dan kegiatan masyarakat, izin mengemudi, izin senjata api, izin usaha jasa keamanan, hingga izin satwa dsb—terkecuali izin pacaran.
Belum lagi kewenangan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kita tentu ingat kasus pengadaan simulator SIM yang menyeret seorang Irjen Polisi ke bui selama 18 tahun. Ia terbukti menerima komisi Rp30 miliar dari proyek itu.
Sebagai informasi, tahun lalu Peninjauan Kembali (PK) yang bersangkutan dikabulkan MA. Meski hukuman penjara tetap 18 tahun dan ganti kerugian negara Rp32 miliar tapi seluruh barang bukti yang disita dan perolehannya sebelum kasus terjadi, diputus dikembalikan kepadanya.
Itulah yang kemudian memunculkan sinisme masyarakat, sebab, jika mengandalkan gaji semata, mana mungkin polisi berharta miliaran. Gaji tertinggi di Polri adalah untuk Jenderal Polisi dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp5,93 juta!
Makanya saya heran ketika pada 15 November 2019 Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM yang intinya larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri.
Pertanyaannya, apanya yang mau dipamerkan kalau gajinya cuma segitu? Lalu, tujuan aturan itu apakah melarang hidup mewah atau hanya melarang pamer hidup mewah?
Ternyata saya bodoh dan salah. ‘Rezeki’ orang bisa dari mana-mana! Satu kekaisaran bisa dapat Rp1,3 triliun/tahun menurut dokumen Konsorsium 303 yang beredar luas itu, mungkin adalah salah satu manifestasi ‘rezeki’ tadi. Meskipun tak bisa disamaratakan, tentu banyak juga polisi ‘proletar’ yang hidup biasa-biasa saja dan sudah cukup bahagia bisa berdedikasi kepada institusi melalui konten-konten Tiktok yang menghibur masyarakat—tidak termasuk terminologi menghibur adalah orang yang goyang tersambo-sambo sambil memuja kegantengan tersangka pembunuhan berencana.
Data terbaru kepatuhan LHKPN menunjukkan ada 16.074 wajib lapor LHKPN di lingkungan Polri. Sebanyak 689 belum lapor sama sekali dan 2.600 laporan belum lengkap.
Selain anggaran yang jumbo, kewenangan yang besar, masih ditambah pula adanya diskresi yang diberikan oleh UU Kepolisian. “… yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan PENILAIAN SENDIRI.”