Oleh: Dr. Mohammad Nasih
Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nashihah MONASH INSTITUTE Semarang, Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ serta Redaktur Ahli Hajinews.id
Al-Qur’an adalah kitab suci dari Allah yang dijamin keasliannya sampai akhir zaman. Ia merupakan salah satu sumber ajaran Islam, di samping hadits (baca: sunnah), yang karena itu harus selalu disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar mereka mengetahui petunjuk jalan yang benar dan mengantarkan kepada keselamatan.
Namun, untuk mengakses al-Qur’an, sesungguhnya bukan perkara mudah. Sebagai bacaan yang diturunkan bukan sebagai tulisan, melainkan mula-mula ditirukan dengan pelafalan dan dihafalkan, dan juga tidak ditulis secara khusus dalam satu bendel buku, tidak banyak kalangan sahabat yang hafal total firman yang sekarang dibagi menjadu 30 juz itu.
Ketika sudah dikumpulkan, pada era Abu Bakar karena ada banyak sahabat penghafal al-Qur’an yang syahid dalam perang Yamamah, dan prosesnya pun alot dimulai dengan usul Umar yang awalnya ditolak oleh Abu Bakar, jumlah mushaf utuhnya hanya satu buah saja. Ketika ditulis ulang di era Utsman, dengan tujuan menghilangkan potensi menimbulkan kesalahpahaman akibat bacaan yang berbeda, jumlah mushaf hanya lima buah saja yang masing-masing dikirim ke Makkah, Syam, Bashrah, dan Kufah. Sementara satu buah lagi dipegang oleh Khalifah Utsman dan disebut sebagai mushaf Imam.
Nah, saat itu, jumlah pemeluk Islam bertambah dengan sangat pesat, sehingga rasio antara jumlah mushaf ditambah dengan penghafal al-Qur’an dan jumlah umat Islam semakin kecil. Ditambah lagi ketika Islam sudah menyebar ke seluruh benua, tentu saja, persoalan menjadi bertambah. Sebab, pemeluk Islam di luar jazirah Arabia tentu saja mengalami kesulitan untuk membaca al-Qur’an. Bahkan sebagian orang Arab sendiri. Karena itulah, sejak era Mu’awiyah, telah dilakukan berbagai upaya agar al-Qur’an bisa sekedar dibaca secara benar, dengan mula-mula menambahkan titik-titik dan pada era kepemimpinan politik terkemudian juga ditambahkan harakat (a, i, u). Sebab, bacaan a, i, u, pada akhir kata, juga ya/yu, ta/tu, a/u, dan na/nu pada awal kata dalam bahasa Arab, bisa menyebabkan perbedaan bahkan pertentangan makna akibat perbedaan subjek.
Tulisan gundul, bagi sebagian orang Arab yang terpelajar bukan masalah. Namun, bagi orang non-Arab, tentu saja secara umum bisa dikatakan menjadi masalah berat. Bahkan saat sudah ada titik dan harakat pun, ternyata masih lebih banyak muslim yang belum bisa membacanya, hatta hari ini. Jika pun bisa membacanya, lebih banyak jumlah yang kualitas tajwidnya belum memenuhi standar.
Sebelum ada mesin cetak oleh Johannes Guttenberg pada tahun 1450-an, penggandaan teks hanya bisa dilakukan secara manual dengan tangan. Bahkan setelah lama ada mesin cetak itu pun al-Qur’an tidak lantas dicetak disebabkan sebagian ulama’ dan juga penguasa menganggap bahwa ayat: Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (al-Waqi’ah: 79) membuat upaya pencetakan yang alatnya berada dalam penguasaan “orang kafir” tidak memungkinkan. Dan pencetakan pertama kali dengan menggunakan mesin cetak juga terdapat kesalahan.
Penggandaan al-Qur’an, karena itu, tentu saja hanya bisa dilakukan dengan tangan kaum muslimin sendiri. Dan ini hanya dilakukan oleh penguasa yang memiliki kepedulian dan/atau ulama’ yang memilikiconcern besar kepada penyebaran ilmu dan dakwah Islam. Tingkat literasi umat Islam tentu saja mengalami masalah yang sangat serius, ditambah lagi dengan pertumbuhan jumlah umat Islam menjadi semakin pesat, baik melalui “jalan perdagangan” maupun penaklukan. Islam menyebar sampai ke benua-benua lain yang tentu saja bukan hanya tidak mengenal tulisannya, tetapi bahkan juga bahasanya.
Usaha peningkatan literasi ini terus dilakukan oleh para penguasa muslim dan ulama’nya dengan berbagai cara. Jika Abu Bakar, Utsman, dan Mu’awiyah dengan kekuasaan melakukan tindakan besar menulis ulang teks lalu memberikan tanda-tanda yang memudahkan, yang sebagiannya sesungguhnya menyulut kontroversi pada awalnya, para ulama’ dengan cara kulturalnya melakukan usaha lain yang tak kalah signifikan untuk menjadikan pembacaan al-Qur’an dilakukan secara massal atau berjama’ah, walaupun tanpa media pendukung berupa teks pada lembaran yang bisa dibaca.
Salah satu upaya tersebut, dan yang saat ini bahkan menjadi tradisi, adalah tahlilan. Tentu saja tahlilan di sini bukan sekedar berarti membaca laa ilaaha illaa Allah, melainkan sebuah aktivitas khusus dengan bacaan-bacaan yang telah ditentukan, yang di antaranya adalah surat al-Ikhlash (dibaca tiga kali), al-Falaq, al-Naas, kemudian berputar lagi ke bagian awal al-Qur’an yaitu al-Faatihah, al-Baqarah: 1-5, lalu melompat ke ayat kursi di halaman awal juz tiga dan diakhiri dengan hampir satu halaman terakhir surat al-Baqarah. Setelah itu ditambah dengan kalimat-kalimat pujian, tasbih, dan juga shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.
Formula lain sebagai bacaan dalam tahlilan adalah al-Fatihah, dilanjutkan ayat kursi, beberapa ayat di akhir surat al-Baqarah, baru melompat ke akhir al-Qur’an dengan membaca al-Ikhlaash (tiga kali), dilanjutkan al-Falaq, dan al-Naas. Kedua formula bacaan tersebut secara substansi bertujuan sama, yakni mengajak umat Islam yang akses mereka kepada al-Qur’an masih sulit, untuk terbiasa dengan bacaan al-Qur’an. Di antara momentum yang paling mendukung adalah saat ada yang meninggal dunia.
Konteks masalah literasi itulah yang sesungguhnya melahirkan “gagasan cerdas” tahlilan. Membiarkan umat Islam dengan jumlah yang terus bertambah, itu berarti membiarkan mereka hidup dengan formalitas agama baru, tetapi tidak mengalami perubahan cara berpikir dan berperilaku. Sebab, ajaran agama baru yang mereka anut, tidak mereka ketahui.
Sementara untuk membuat mereka bisa membaca al-Qur’an 30 juz, tentu saja “tidak mungkin”. Muncullah Imam Sayyid Abdullah Bin Alwi al- Haddad (w 1718M, 1132M) di Tarim, Yaman, yang menyusun formula tahlilan. Entah mengikuti Sayyid Abdullah atau dengan ide sendiri, di kemudian hari muncul juga Sayyid Ja’far al-Barzanji (w. 1766M, 1177H) yang melakukan hal yang kira-kira sama. Al-Barzanji merupakan nisbah kepada sebuah kampung di kawasan Akrad, Kurdistan, bernama Barzanjiyah. Jika melihat nisbah Barzanjiyah, maka tempat antara kedua ulama’ ini relatif jauh. Namun, jika melihat bahwa sesungguhnya al-Barzanji lahir dan meninggal di Madinah, maka keduanya berada di dua kota yang jaraknya terpotong kira-kira separuhnya. Dengan pertimbangan itu, sangat mungkin al-Barzanji mengikuti yang dilakukan Sayyid Abdullah.
Membaca formula tahlilan yang di dalamnya terdapat rumpun-rumpun ayat di awal dan di akhir al-Qur’an akan terbentuk simbol pembacaan keseluruhannya. Patut diduga kuat bahwa pandangan itu didasarkan pada sebuah hadits bahwa bacaan surat al-Ikhlash bernilai sama dengan sepertiga al-Qur’an. Dengan demikian, pemahaman simplistis akan mengantarkan pada simpulan bahwa membacanya tiga kali sama dengan membaca keseluruhan al-Qur’an. Dan pandangan itu sudah ada di kalangan muslim jauh sebelum kedua ulama’ pencetus tahlilan itu lahir.
Tentu saja perspektif kritis terhadap pemahaman simplistis tentang hadits tersebut tidak sedikit. Di antaranya dari Imam al-Ghazali, yang menganggap bahwa pemahaman mengenai hadits tentang surat al-Ikhlash tersebut tidak tepat. Namun, masing-masing pejuang dakwah Islam menghadapi dinamika sosial masyarakat sendiri-sendiri dan sangat mungkin mengambil ijtidah yang berbeda karena dirasa lebih tepat dalam konteks di masa hidupnya.
Keadaan ummat menuntut pendakwah ummat membangun strategi dakwak berbasis hikmah (dalam makna sederhana kebijaksanaan). Sebab, mengatakan kebenaran, seringkali sulit, bahkan tidak bisa diterima, jika tidak dilambari dengan sikap bijaksana. Konteks keadaan lingkungan yang menjadi latar belakang harus benar-benar mendapatkan perhatian.
Dalam konteks untuk membangun kedekatan dengan al-Qur’an, jalan utama yang harus ditempuh adalah membacanya. Namun, dalam konteks saat itu, dengan media teks tertulis yang sangat terbatas, tentu saja tidak mungkin membacanya secara keseluruhan. Sebab, untuk melakukannya, terutama pada saat itu, diperlukan kapasitas yang jauh di atas rata-rata, terutama memiliki daya ingat level mendekati dlabit. Sebab, memang tidak ada medianya sebagaimana dinikmati umat Islam sekarang karena al-Qur’an sudah digandakan secara besar-besaran, baik dalam bentuk mushaf konvensional, maupun digital yang bisa dibawa ke mana pun dan kapan pun karena sudah menyatu dengan alat komunikasi.
Karena itu, menganggap tahlilan sebagai bid’ah hanya karena tidak dilakukan oleh Rasululullah, tentu saja menjadi tidak bijaksana. Secara sederhana lagi, itu sama dengan menganggap bahwa Abu Bakar dan apalagi Umar juga melakukan bid’ah disebabkan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Namun, justru karena visi yang jauh Umar melihat situasi dan kondisi saat itu, umat Islam sekarang menikmatinya, dan baik yang tahu sejarahnya maupun tidak, tidak ada lagi yang memandangnya sebagaibid’ah dlalaalah.
Dengan adanya media sebagaimana sekarang, perjuangan peningkatan literasi kepada al-Qur’an harus diteruskan dan bahkan digencarkan. Jangan sampai umat Islam merasa bahwa dengan membaca beberapa penggal rumpun ayat al-Qur’an, lalu merasa segala urusan telah terselesaikan.
Kesadaran ilmiah bahwa al-Qur’an bukan sekedar sebagai sarana mengirim do’a kepada sanak saudara yang sudah meninggal, misalnya, harus dibangkitkan dan diperkuat agar al-Qur’an selalu mendatangkan daya untuk kemajuan umat Islam. Sebab, hanya dengan membaca dan memahami keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an, panduan untuk seluruh aspek kehidupan, baik politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, bahkan juga sains dan teknologi bisa ditemukan. Pemahaman itulah yang diharapkan menjadi daya dorong bagi kaum muslim untuk kembali memimpin peradaban dunia.
Tahlilan harus digalakkan sebagai sarana dakwah awal kepada mereka yang belum memiliki akses kepada al-Qur’an. Itu harus dianggap sebagai salah satu cara saja untuk mendekatkan dan membiasakan umat Islam kepada kitab suci sendiri.
Setelah mereka terbiasa dengan bacaan sebagian kecil ayat-ayat di dalam al-Qur’an, mereka harus didorong lebih jauh untuk membaca keseluruhannya lalu memahami maknanya semakin mendalam. Tidak boleh berhenti sampai di situ, karena harus menjadikan al-Qur’an sebagai sumber inspirasi bagi temuan-temuan saintek baru yang merupakan indikator paling konkret dalam peradaban. Wallaahu a’lam bi al-shawaab.














































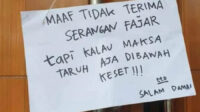




































1 Komentar