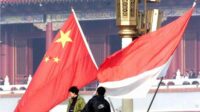Oleh: Dipo Alam
Hajinews.id – Sejak berita duka itu beredar pada Minggu siang, 18 September 2022 lalu, telah banyak tulisan obituari untuk mengenangkan sosok Azyumardi Azra, baik terkait pribadi, pemikiran, maupun reputasi intelektualnya yang mendunia. Saya tidak ingin menggarami air laut. Sebagai anggota Institut Peradaban, saya hanya ingin membuat catatan kecil mengenai irisan sosok Azyumardi dengan isu peradaban.
Dalam dua puluh lima tahun terakhir, rasanya tak ada intelektual yang kematiannya pernah ditangisi oleh begitu banyak orang sebagaimana Azyumardi Azra. Hampir semua surat kabar nasional menjadikannya berita halaman muka dalam porsi besar dan mendedikasikan tajuknya untuk menuliskan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut.
Tentu saja orang akan mengajukan nama Cak Nur, senior Azyumardi, ataupun Gus Dur. Namun, berbeda dengan Cak Nur dan Gus Dur, Azyumardi tidak pernah menjadi pejabat tinggi negara, tokoh politik, atau calon presiden. Ia juga tidak pernah menjadi anggota kabinet, anggota parlemen, atau pimpinan partai politik.
Berbeda dengan Cak Nur yang pernah dua periode jadi Ketua Umum PB HMI, atau Gus Dur dan Syafii Maarif yang masing-masing pernah jadi Ketua Umum PBNU dan PP Muhammadiyah, Azyumardi juga tidak pernah memimpin organisasi massa besar. Di Muhammadiyah, misalnya, posisi terakhirnya adalah Anggota Konsultan Ahli di Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah.
Artinya, kiprah Azyumardi di ruang publik, sejak muda hingga akhir hayatnya, selalu berada di ranah intelektual murni. Sehingga, seluruh penghormatan yang kita saksikan diberikan kepadanya dalam beberapa hari terakhir hingga hari-hari mendatang, adalah penghormatan terhadap reputasi dan jejak intelektualnya. Dan itu, menurut saya, adalah bentuk penghormatan yang sangat luar biasa. Sebab, sekali lagi, hanya sedikit sekali intelektual yang pernah mendapat penghormatan semacam itu.
Kenapa Azyumardi bisa mendapat penghormatan demikian besar?
Jawabannya pastilah tidak tunggal dan pendek. Namun, saya ingin mencatat, sebagai intelektual, terutama dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Azyumardi telah mendedikasikan seluruh reputasi intelektualnya yang menjulang untuk menyuarakan dan membela kegelisahan publik. Di era Presiden Joko Widodo, ini bukanlah sebuah pilihan pertaruhan yang mudah.
Dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, Joko Widodo memang adalah presiden paling lemah, karena tidak memiliki basis kekuasaan politik. Ia tidak pernah punya akar dan posisi yang kuat di partainya. Ia juga bukan mantan aktivis, pemimpin organisasi massa, atau pemuka masyarakat yang punya jejaring politik luas. Sehingga, ketika naik ke puncak kekuasaan, para penyokongnya telah menyulap simpul-simpul lain di luar partai politik dan organisasi massa untuk dijadikan basis massa bagi kekuasaannya. Dan salah satu basis massa itu adalah perguruan tinggi.
Inilah yang menjelaskan kenapa di era Presiden Joko Widodo ikatan alumni dan organisasi relawan tiba-tiba menjelma jadi organisasi politik. Keduanya muncul, atau lebih tepatnya dimunculkan, karena presiden memang tidak memiliki basis kekuasaan. Maraknya kelompok-kelompok penekan yang mengatasnamakan alumni-alumni kampus dan organisasi relawan dalam delapan tahun terakhir adalah bagian dari fenomena ini.
Berbeda dengan masa Orde Baru, di mana rekrutmen orang-orang perguruan tinggi dilakukan untuk alasan teknokrasi, maka di era Presiden Joko Widodo rekrutmen orang-orang perguruan tinggi dilakukan untuk membangun basis kekuasaan pemerintah. Celakanya, sejumlah akademisi kampus secara tak senonoh telah memanfaatkan peluang ini dengan menjadikan kampusnya sebagai kendaraan politik untuk meraih jabatan-jabatan pemerintahan. Mereka ingin berpolitik, tapi enggan masuk partai politik. Ingin kebagian jabatan-jabatan politik, tapi enggan disebut politisi. Ini juga yang menjelaskan kenapa berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, gerakan mahasiswa dan suara kritis dari kampus seolah telah meredup di era Presiden Joko Widodo.
Kita mungkin masih ingat, dua tahun silam seorang profesor dari sebuah perguruan tinggi negeri yang kini menjadi staf khusus di sebuah kementerian pernah melontarkan pernyataan yang menghina kegiatan demonstrasi sebagai seolah kegiatan kurang beradab. Intelektual yang berdemonstrasi, menurutnya, pastilah orang yang lemah dalam berargumentasi dan lebih senang menikmati budaya grudak-gruduk. Terus terang itu pernyataan yang mengherankan, apalagi yang melontarkannya kebetulan juga seorang guru besar dalam rumpun ilmu sosial.
Intelektual ikut berdemonstrasi, atau bahkan menggagas serta memelopori demonstrasi, sebenarnya bukanlah hal aneh dan baru. Bahkan, yang pernah terlibat melakukannya juga bukan orang-orang sembarangan.
Sebagaimana terekam dalam sejumlah foto yang kini telah menjadi klasik, pada 1972 Foucault dan Sartre terlibat dalam sebuah demonstrasi di depan Kementerian Kehakiman Perancis guna membela hak-hak kaum imigran. Siapa tak kenal Jean-Paul Sartre? Siapa juga tak kenal Michel Foucault? Apa keduanya terlihat seperti orang yang kekurangan akal dan suka grudak-gruduk?
Linus Carl Pauling adalah seorang intelektual yang pernah memenangi dua hadiah Nobel, yaitu Nobel Kimia (1954) dan Nobel Perdamaian (1962). Penghargaan itu menunjukkan bagaimana reputasinya sebagai seorang sarjana. Pada 1962, Pauling terekam kamera ikut dalam sebuah aksi demonstrasi yang diikuti oleh ratusan orang di depan Gedung Putih, mereka menolak dimulainya kembali uji coba nuklir di semua wilayah Amerika. Apakah Pauling terlihat seperti orang fakir baku-dalih?
Terlibat atau tidak terlibat dalam sebuah demonstrasi bukanlah perkara besar dan kecilnya otak seseorang, melainkan lebih soal kepekaan nurani seseorang. Seorang intelektual yang terusik nuraninya, bukan hanya boleh, atau harus ikut berdemonstrasi dan berorasi, bahkan bila perlu ikut melempar batu sebagaimana yang pernah dilakukan Edward Said. Pada tahun 2000, dalam sebuah aksi membela Palestina di perbatasan Lebanon-Israel, Said ikut melempari batu pos-pos tentara Israel.
Apakah aksi itu telah menurunkan derajat Edward Said menjadi seorang tukang gruduk, atau justru menunjukkan kepekaan nuraninya yang tak sekadar hidup di menara gading?
Upaya untuk mengkooptasi kampus sebagai basis massa kekuasaan ini secara efektif telah membungkam kampus dan para intelektual di dalamnya. Hanya sedikit sekali dari mereka, terutama yang masih aktif mengajar dan memiliki jabatan di kampusnya, yang berani melontarkan suara kritis kepada pemerintah. Dan Azyumardi adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Suaranya terdengar sangat nyaring dalam beberapa tahun terakhir karena banyak dari koleganya memilih untuk bungkam dan tutup telinga.
Pada tahun 2017, misalnya, ketika Presiden Joko Widodo meresmikan tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Azyumardi dengan lantang mengkritik bahwa penetapan itu lebih bermakna politis daripada akademis. Sebab, menurutnya, yang lebih tepat untuk ditetapkan sebagai pintu masuknya Islam ke Nusantara adalah Aceh.
Saya mencatat, Azyumardi aktif terlibat dalam sejumlah isu yang melahirkan polemik di tengah masyarakat, mulai dari Revisi UU KPK, resentralisasi kekuasaan, bahaya oligarki, pemindahan ibukota, pendirian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), hingga soal reformasi Polri.
Secara umum Azyumardi menilai jika praktik demokrasi di Indonesia terus mengalami kemerosotan akibat terjadinya peningkatan peran oligarki. Ia menilai bahwa dunia politik Indonesia kini disetir oleh oligarki. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dari perubahan sejumlah undang-undang, mulai dari undang-undang mineral, undang-uncang Cipta Kerja, hingga undang-undang Ibukota Negara yang dinilai hanya menguntungkan para oligarki.
Sebagai akademisi, Azyumardi juga mengkritik keras peleburan berbagai lembaga riset ke dalam BRIN. Ia terutama menyoroti struktur dewan penasehat dan dewan pengarah BRIN yang dominan oleh figur politisi, dan bukannya peneliti. Menurutnya, dewan pengarah BRIN harus terdiri orang yang punya nama dalam riset dan inovasi, bukan politisi, bukan juga pengusaha.
Terkait peleburan LIPI hingga Lembaga Eijkman ke dalam BRIN, Azyumardi menyebut hal itu sebagai malapetaka bagi dunia riset dan inovasi di Indonesia. Adanya peleburan tersebut justru telah mendestruksi lembaga riset dan membuat sumber daya peneliti jadi tercera-berai.