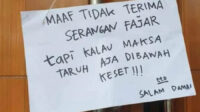Etika politik juga penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (partai) dan mendukung pembentukan berbagai kebijakan publik yang adil serta berkelanjutan.
Itu sebabnya, etika politik menjadi penting untuk mencegah kontra-nilai atau anti-etik yang sering disebut sebagai perilaku politik Machiavelli.
Meminjam Niccolò Machiavelli, melalui karyanya “The Prince” anti-etik disebut sebagai cara mencapai dan mempertahankan kekuasaan, dengan cara apa saja, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang dianggap tidak bermoral sekalipun menjadi sah dan wajar.
Lantas bagaimana etika politik digunakan untuk mencermati perangai politik dan sejumlah keputusan politik Jokowi, terutama dalam relasi politiknya dengan PDIP (Megawati) belakangan ini?
Bila mau jujur, sesungguhnya ada persoalan mendasar pada etika politik yang perlu menjadi titik tekan. Pentingnya kebiasaan baik dan juga karakter dalam kepemimpinan politik sebagai landasan etika politik telah diabaikan atau tak diindahkan.
Apa yang tersaji memperlihatkan Jokowi seakan tidak memperlakukan dan atau menempatkan PDIP sebagai entitas politik yang penting dan wajib dihormati sebagai penyokong utamanya dalam merengkuh kekuasaan.
Sikap politik itu ditunjukan dan justru terjadi ketika atau setelah Jokowi telah mendapat relasi serta kawan politik yang baru (partai-partai) di luar PDIP.
Seakan ada amnesia, dalam konteks karier politik elektoral Jokowi yang panjang selama lebih dari 22 tahun, tak terlepas dari kontribusi besar PDIP.
Fakta politik yang tak terbantahkan, Jokowi bisa 10 tahun menjadi Wali Kota Solo, 2 tahun lebih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hampir 10 tahun menjadi Presiden Indonesia adalah mahakarya politik PDIP.
Tentu saja, karena di negara demokrasi-konstitusi seperti Indonesia, akan sulit seseorang bisa punya karier politik yang panjang dan berjenjang, dari level bawah hingga atas, tanpa dukungan dari partai.
Itu artinya, seseorang sekalipun dengan modal elektabilitas yang tinggi, tidak akan bisa berkontestasi, hingga menang dalam kandidasi presiden dan wakil presiden tanpa diusung oleh partai.
Dalam kalkulasi ini, Jokowi mungkin saja akan tetap menjadi pengusaha mebel di Kota Solo, andai saja PDIP tak pernah mengusungnya menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Tanpa PDIP, Jokowi bukan siapa-siapa di perpolitikan Indonesia.
Betul, Jokowi juga memberikan kontribusi atau efek ekor jas atau coat-tail effect ke PDIP, terutama dalam pemilu terakhir (2019), tapi itu bukan sesuatu yang signifikan, karena sebelum era Jokowi pun PDIP sudah merupakan salah satu partai besar di Indonesia.
Pada pemilu 2014, PDIP adalah partai papan atas, meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95 persen, yang kemudian menjadi modal untuk mencalonkan Jokowi dalam Pilpres 2014.
Sehingga bila kemudian pada HUT PDIP di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, lantas ia tak menyempatkan waktu hadir, tentu menjadi wajar kemudian dipertanyakan secara etika politik.
Apalagi pada hari-hari sebelumnya, lewat media massa maupun melalui media sosial, nampak Jokowi meluangkan waktu untuk makan dengan sejumlah pimpinan partai. Masa iya, dengan PDIP sebagai rumah politiknya, Jokowi malah justru menjauh.
Jokowi diketahui makan malam dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di Menteng Jakarta, Jumat (5/1), sarapan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Sabtu (6/1), serta makan siang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Medja Restoran di Kota Bogor, Minggu (7/1).