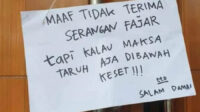Oleh
Jusuf Kalla
Mantan Ketua Umum Partai Golkar
PARTAI politik adalah instrumen fundamental dalam suatu sistem demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, kunci demokrasi ada pada partisipasi rakyat.
Kalau partai politik ingin menjadi bagian dari demokrasi, partai itu harus demokratis. Sebab, tidak mungkin sebagai instrumen pokok demokrasi partainya malah tidak demokratis.
Kita sudah hidup di era yang berbeda.
Zaman dulu, kalau ada pemilu, sudah banyak yang mengatur hingga selesai. Mulai bupati, camat, babinsa, hingga elemen lain. Partai, khususnya Golkar, tinggal terima jadi. Partai lain di luar Golkar harus berjuang di tengah persaingan yang ketat. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi.
Kalau kita lihat sekarang, sangat berbeda. Babinsa harus netral. Pegawai negeri, aparatur sipil negara, tidak boleh berpartai. Padahal, dulu pegawai negeri itu berbaju kuning (Golkar). Tentara dulu juga ada yang berbaju kuning. Maka, kita bisa melihat Golkar sekarang.
Suara Golkar yang pada 1992 mencapai 67 (68) persen, lalu terakhir 1997 menjadi 74 persen, setelah reformasi turun menjadi 20-an persen. Sekarang, di Pemilu 2019, malah menjadi 12 persen. Kita bisa membayangkan seberapa tajam penurunannya.
Saya ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman saya saat memimpin Golkar pada 2004–2009. Partai harus demokratis lebih dahulu sebelum mengambil peran dalam demokrasi Indonesia. Dan saya konsekuen soal itu. Pada era saya, pengurus partai, dalam hal ini pengurus harian, tiap bulan harus rapat. Kemudian, pleno diselenggarakan rutin setiap tiga bulan.
Saat itu kepengurusan sengaja saya buat ramping untuk memudahkan dalam bergerak. Saat itu pengurus harian berjumlah 33 orang dan untuk rapat pleno dihadiri 90 orang. Sekarang hampir 300. Sehingga dinamika menjadi begitu banyak dan berat. Dampaknya, rapat pengurus harian menjadi jarang, apalagi pleno.
Di era kepengurusan saya, semua keputusan yang penting harus berdasar hasil rapat. Tidak ada penunjukan langsung dari saya. Ketua DPD atau pengurus fraksi di DPR ditentukan secara terbuka dalam forum rapat. Kami bahas bersama-sama. Kalau tidak terjadi mufakat, diambil langkah voting.
Saat itu kami juga sangat hati-hati dalam menentukan pengurus. Kami memilih pengurus yang tidak mempunyai cacat atau berita cacat. Bila ada indikasi masalah, langsung dicoret dari pencalonan. Aturan itu berlaku kepada siapa pun, termasuk teman baik saya. Sehingga partai bersih dari hal-hal itu. Kita bisa membuat demokrasi yang baik kalau partai itu bersih.
Ada catatan penting di era saya mengenai rangkap jabatan. Kami benar-benar memisahkan anggota DPR dari pengurus partai. Demikian pula dengan menteri di kabinet. Meskipun, saat itu saya Wapres sekaligus ketua umum. Yang sempat rangkap saat itu adalah menteri kesehatan.
Saat itu Golkar memberlakukan aturan, anggota DPR tidak boleh menyetor ke DPP. Karena itu, anggota DPR juga tidak boleh mencampuri proyek-proyek pemerintah dan mengambil manfaat dari proyek-proyek itu. Bukannya sekadar tidak bisa, namun tidak boleh.
Untuk urusan pendanaan partai, saya menekankan partai harus hidup sederhana. Kami punya bermacam-macam anggota yang mampu menyumbang dan sifatnya halal. Bisa dari sponsor atau sumbangan pendukung. Bukan atas nama proyek atau anggaran. Sehingga tidak satu pun anggota Partai Golkar yang berurusan dengan hukum dari kepengurusan 2004–2009.
Demokratisasi juga harus berlaku pada jajaran di daerah. Saya beberapa bulan lalu pulang ke Makassar dan bertemu semua pimpinan partai di Makassar. Ada seorang pimpinan partai, bukan Golkar, curhat kepada saya. Dia bilang, DPP itu sekarang seperti malaikat maut. Karena ia yang menentukan segala-galanya. Kalau ada yang tidak setuju atau tidak sejalan, akan di-Plt-kan.
Pada kenyataannya, hal-hal semacam itu ada di hampir semua partai. Termasuk Golkar. Dan itu terjadi, kalau di Golkar, luar biasa banyaknya. Calon-calon anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota, semua ditentukan oleh DPP. Tidak ada peran dari mereka yang duduk di DPD atau DPC. Semuanya keputusan ketua umum dan Sekjen.
Itu harus menjadi perhatian. Jangan sampai diktator zaman dulu pindah ke partai. Waktu kepengurusan saya, semua keputusan yang menyangkut struktur partai ke bawah harus melibatkan pengurus di bawahnya. Tidak boleh ada penunjukan langsung.
Kalau ingin pencalonan gubernur, suara pusat hanya dihitung 40 persen, DPD tingkat I 40 persen dan DPD tingkat II 20 persen. Sementara itu, untuk pencalonan bupati atau wali kota, dibalik. DPD tingkat II suaranya 40 persen dan DPP hanya 20 persen.
Komposisi itu hanya akan digunakan bila jalan musyawarah mufakat tidak berhasil sehingga harus voting. Dengan cara itu, tidak ada kesempatan bagi DPP untuk berlaku otoriter. Juga tidak ada mahar politik. Kalau yang memutuskan adalah tiga kepala, tidak ada kesempatan untuk memberikan mahar politik.
Kita harus sama-sama ingat. Di Lapas Sukamiskin, sudah ada empat mantan ketua umum partai. Dari Golkar, PPP, Demokrat, dan PKS. Bagaimana kita bisa menawarkan demokrasi kepada rakyat kalau di internal partai sendiri masih ada yang semacam itu. Apalagi bicara pemerintahan yang bersih.
Sudah saatnya semua partai, khususnya Golkar, lebih fokus. Ketika kadernya terpilih sebagai anggota legislatif, biar mereka fokus bekerja. Sementara partai harus menjadi ormas. Dalam arti turun dan terlibat bersama rakyat sepanjang waktu. Jangan ketika mau pemilu saja mendekati rakyat. Karena rakyat kita sekarang juga tidak bodoh.
Siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar pada munas kali ini, saya yakin bisa menjadikan partai ini kembali demokratis. Kuncinya adalah kemauan untuk membuat sebuah sistem yang demokratis hingga ke tingkat bawah.
Sistemnya juga tidak perlu rumit karena lingkupnya adalah internal partai. Bisa dimulai dari setiap keputusan didasarkan pada hasil rapat. Kemudian, penunjukan calon kepala dearah melibatkan DPD dan DPC. Itu bagian dari upaya membuat partai ini lebih demokratis.
*Disarikan dari pidato Jusuf Kalla dalam Diskusi Publik Golkar ”Memperkuat Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia”